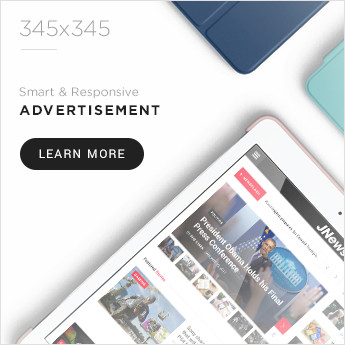Di tengah ramainya pembicaraan soal patriarki, feminisme, misogini, dan emansipasi, posisi perempuan sering kali menjadi pembahasan utama. Ironisnya, tak semua perempuan benar-benar memahami dirinya sendiri untuk turut memperjelas posisinya dalam berbagai diskursus tersebut.
Di satu pihak, sebagian perempuan terus mengupayakan kesetaraan dengan pendekatannya masing-masing. Di sisi lain, tak sedikit perempuan yang memilih menepi dan memberi ruang lebih untuk laki-laki, seperti mundur dari kesempatan belajar atau memimpin. Bahkan, entah berapa banyak perempuan yang lebih suka memoles penampilan fisiknya, alih-alih pemikiran atau kemampuannya.
Dalam bukunya yang berjudul Perempuan, M Quraisy Shihab, mengingatkan bahwa perempuan sendiri perlu memahami hak dan tanggung jawabnya. “… perempuan tidak hanya harus merasa diri setara dengan lelaki, tetapi lebih dari itu, perempuan harus membuktikan hal tersebut melalui kemampuannya dalam dunia nyata.”
Sebagai perempuan, hal ini menjadi PR yang cukup kompleks. Sudah umum diketahui bahwa meskipun setara, laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda. Salah-salah, langkah yang diupayakan malah terlampau ekstrem karena menyamakan diri sepenuhnya dengan lelaki. Terkait hal ini, sudah selayaknya kita berpegang pada tuntunan Tuhan, muasal diciptakannya perbedaan itu. Di sanalah ditemukan penegasan tupoksi keduanya —mana yang boleh dan tak boleh, mana yang seharusnya dipisahkan dan disatukan, mana yang semestinya dibedakan dan selayaknya disamakan.
Sayangnya, narasi agama sering menuntut adanya upaya lain agar tak lagi rawan disalah pahami. Memang, sudah banyak buku atau kajian yang berusaha memberi penafsiran secara gamblang. Namun, upaya ini masih sering dipandang kaku dan sulit membumi. Dalam hal ini, keragaman narasi dalam berbagai bentuk dan rupa bisa menjadi sarana penting untuk mempertegas posisi dan kedudukan perempuan, terutama yang berpijak dari sudut pandang perempuan sendiri.
Senada dengan hal tersebut, Al-Jauzi, melalui pengantar kitab Sifat As Shofwah dalam menanggapi kitab Hilyatul Auliya’, mengkritik minimnya penyebutan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah peradaban Islam. Alasannya, hal ini dapat mendongkrak motivasi pembacanya, termasuk laki-laki. Dalam kitab tersebut, Al-Jauzi menyertakan 200 kisah singkat dari tokoh-tokoh perempuan, jauh lebih banyak dari Hilyatul Auliya’ yang hanya menyertakan 20 tokoh. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya Islam tidak kurang teladan perempuan. Baca Juga Keistimewaan Perempuan dalam Islam
Kita telah mengenal nama-nama besar seperti Ibunda Aisyah RA yang mempunyai sumbangsih dalam kemajuan peradaban Islam melalui periwayatan ribuan Hadits, Rabi’ah Al-Adawiyyah yang mencintai Sang Rabb sebegitu dalam, atau Sayyidah Nafisah yang merupakan guru dari guru kita, Imam As-Syafi’i. Jika mau melompat lebih jauh, ada juga Fatimah Al-Fihri yang merupakan perintis perguruan tinggi dalam dunia Islam, atau Nyai Khoiriyah Hasyim yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan pendidikan perempuan.
Namun, kita tak memerlukan sekadar deretan nama, jabatan, serta tanggal kelahiran dan tanggal wafat. Lebih dari itu, dibutuhkan lebih banyak narasi yang mampu menyentuh dan menggerakkan hati agar dapat mengungkap siapa dan seperti apa mereka sebenarnya.
Jika bicara tentang narasi yang melibatkan tokoh lelaki, ada begitu banyak nama yang hadir dalam berbagai literatur. Selain buku-buku sejarah, banyak pula syair, puisi, dan prosa, seperti novel biografi atau sejarah yang menyoroti kehidupan kalangan laki-laki, termasuk yang merekam peradaban Islam secara khusus. Mulai dari kisah para nabi, penakluk dan pemimpin besar kerajaan Islam seperti Sultan Muhammad Al-Fatih atau Harun Al-Rasyid, hingga ulama dan pahlawan nasional seperti Buya Hamka atau KH M Hasyim Asy’ari.
Dalam perkembangannya, juga lahir banyak karya-karya sejenis yang berorientasi penuh pada dunia fiksi, namun masih dengan cerita yang berpedoman nilai islami. Baik cerita nyata atau karya fiksi, semuanya menawarkan berbagai macam karakter yang bisa dijadikan role model. Terkait sifat-sifat umum manusia, tentu tak masalah jika diteladankan juga oleh perempuan.
Masalahnya, pada persoalan yang —mau tak mau— harus mempertimbangkan gender, perempuan tak bisa serta merta meniru sifat para tokoh begitu saja, misalnya dalam meneladani kisah sahabat yang adil dalam memperlakukan istri, atau dalam meniru semangat seorang perantau yang, dengan tekad luar biasa, menempuh perjalanan seorang diri tanpa peduli harus bermalam di mana pun.
Bagaimanapun, perbedaan jenis kelamin meniscayakan perbedaan peran, hak, dan tanggung jawab. Meskipun keduanya setara, perempuan masih sering clue less untuk menetapkan panutan yang tepat dan relevan dalam berbagai segi kehidupan.Oleh karenanya, mereka pun cenderung mengambil jalan aman. Akibatnya, muncul batasan-batasan yang belum tentu berasal dari agama, tetapi justru dibuat sendiri karena ketidaktahuan.
Saat ini, literatur yang berpusat pada tokoh perempuan bukannya nihil. Namun, masih diperlukan narasi yang lebih banyak dan beragam terkait hal ini, agar orientasi perempuan tak melulu soal romansa, perjodohan, atau poligami.
Bagaimanapun, menjadi perempuan juga tentang mengejar mimpi, menjadi berdaya, atau terlibat dalam pengembangan umat sambil tetap mengindahkan nilai-nilai syar’i. Manusia menyukai narasi yang dekat dengan kehidupan. Semakin seseorang merasa terhubung dengan sesuatu, semakin besar kemungkinannya untuk menjadikannya acuan dalam menghadapi persoalan serupa.
Melihat lahirnya beraneka karya yang menyoroti kehidupan laki-laki, maka bukan tak mungkin kisah hidup para tokoh perempuan juga disajikan dengan lebih menarik dan menginspirasi. Narasi-narasi semacam ini diharapkan dapat menjadi teladan nyata —contoh konkrit— terlebih bagi perempuan yang hingga kini masih meraba peran dan posisi masing-masing dalam setiap aspek kehidupan, baik sebagai individu, pasangan, maupun bagian dari masyarakat.
*) Vika Nailul R, pengajar di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Muballighin Blitar sekaligus Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sumber: https://jatim.nu.or.id/